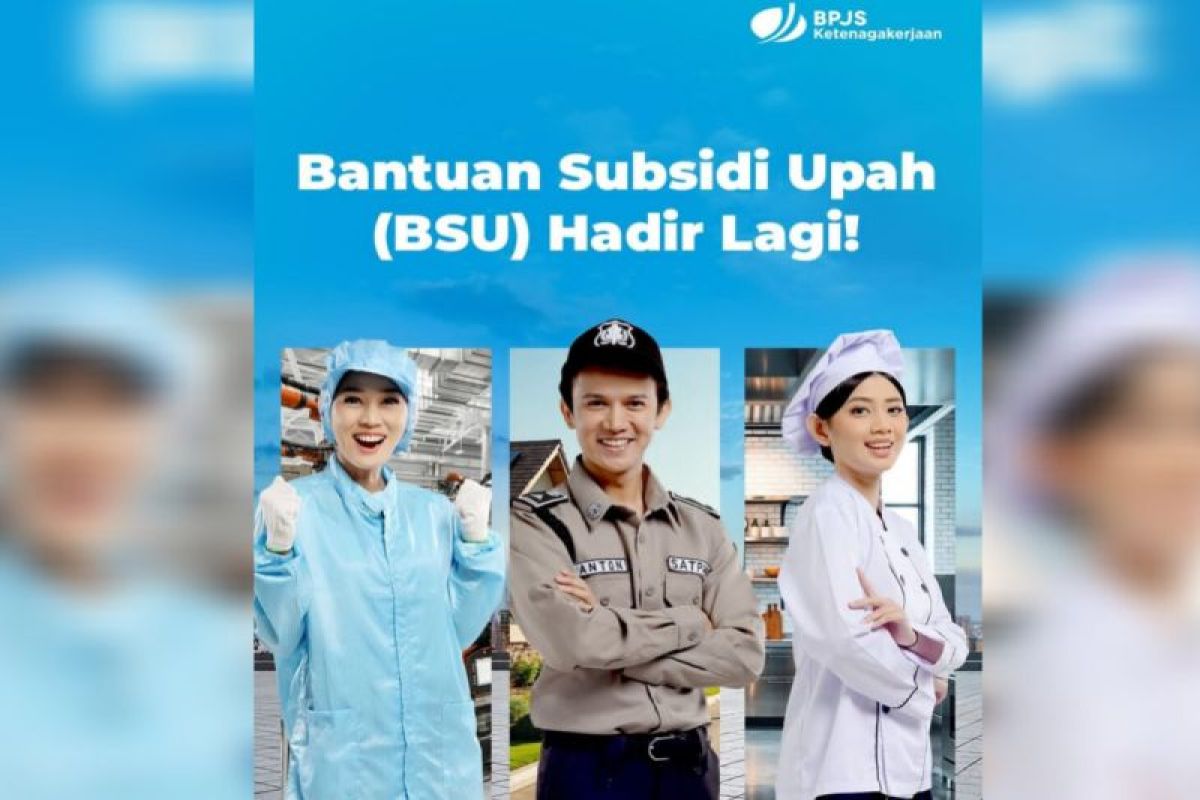Guru Besar Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Maryono dikenal sebagai pegiat pelestarian sungai di Jogja. Dekan Sekolah Vokasi UGM ini telah menerbitkan beragam karya tentang sungai dan terlibat di berbagai gerakan sosial. Agus Maryono mengisahkan perjalanan hidupnya mencintai sungai. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani dan Andreas Yuda Pramono.
Suatu malam di medio 1982, Agus Maryono bermimpi. Ia melihat air bah dalam legenda Nabi Nuh. Mimpi itu datang tak lama setelah ia Salat Istikharah. Agus kala itu bimbang memilih jurusan saat memulai kuliah di Kampus Biru. Apakah ia harus memilih jurusan teknik bangunan atau teknik lainnya.
“Mimpi saya itu melihat air bah Nabi Nuh, makanya saya kemudian mengambil jurusan Teknik Pengairan,” ungkap pria kelahiran 1963 itu ditemui Rabu (15/10/2025).
Jauh sebelum mimpi tentang air bah Nabi Nuh, Agus ternyata sudah sejak lama dekat dengan air, sungai dan pengairan. Ayahnya seorang mantri pengairan di Sukoharjo, Jawa Tengah pada era 1970-an. Agus kecil saat itu sering diajak sang ayah mengecek lokasi pengairan.
“Saya jadi tahu soal air, pengairan. Selain itu kita dulu masih kecil kan biasa main di sungai,” ungkap doktor lulusan University of Karlsruhe, Jerman itu.
Kecintaan Agus pada sungai semakin kuat setelah menjadi mahasiswa. Tak hanya belajar di kelas, ketika terjun ke lapangan aktivitas sosial terkait sungai pun biasa ia lakukan. Ia bercerita kisahnya membangun akses air bersih untuk warga.
“Sewaktu saya mengikuti kuliah kerja nyata [KKN] di Desa Tugurejo, Tempuran, Magelang, warga di sana masih menggunakan air sungai untuk mandi, wudu, warna airnya kuning,” kata penerima penghargaan Kalpataru pada 2015 itu.
Ia bertanya ke warga di mana lokasi sumber air terdekat. Letaknya hanya dua kilometer dari permukiman. Di sana Agus lantas memutuskan membuat saluran air bersih menggunakan bambu sampai ke permukiman warga.
Raut wajah bahagia warga ketika mandi di bawah pancuran air bersih [tak lagi berwarna kuning] membekas di benak Agus. Ia semakin jatuh cinta pada air.
“Singkat cerita saya jadi dosen di Sekolah Vokasi dan kemudian dapat beasiswa ke Austria terus ke Jerman. Di Jerman saya sudah bergerak di upaya-upaya restorasi sungai,” katanya.
Salah satu konsep restorasi sungai saat itu adalah menjadikan sungai kembali seperti bentuk naturalnya, tanpa dam atau talut yang mengubah bentuk dan alur atau morfologi sungai. Proyek dam atau talut menggunakan beton dianggap merusak sungai karena beton menutup mata air yang berasal dari pinggir sungai.
Keberadaan dam juga mengganggu alur migrasi ikan-ikan tertentu yang naik turun melintasi sungai. Terganggunya migrasi fauna di sungai potensial menyebabkan spesies tertentu di sungai punah.
“Kalau di Sungai Code, ada ikan naik turun. Sidat contohnya yang melakukan migrasi. [Restorasi sungai] bisa sekalian penyelamatan populasi sidat. Sidat bisa kembali kalau lingkungannya alamiah,” tutur dia.
Perubahan morfologi sungai karena dibeton lewat proyek talut dan dam juga menyebabkan lintasan sungai menjadi deras di titik-titik tertentu sehingga erosi semakin banyak di bagian hilir dan bahkan bisa menggerus bangunan seperti tiang jembatan. Kondisi ini juga menyebabkan sedimentasi di bagian hilir semakin masif dan mendorong proyek pengerukan sungai berbiaya mahal.
Dalam konteks seperti Sungai Code di Jogja yang berhulu di Merapi, keberadaan dam menurut Agus justru menghalangi aliran pasir Merapi secara alami berujung ke laut. Padahal keberadaan pasir tersebut berguna sebagai filter polutan di air sungai. Pasir-pasir yang mengalir alami di sepanjang sungai itu menurut Agus juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk penambangan skala kecil yang tidak merusak lingkungan.
Gagasan restorasi sungai di negara-negara maju bahkan sudah ada sejak medio 1980-an. Itu kenapa, proyek infrastruktur seperti dam di negara-negara Eropa sudah ditinggalkan sejak lama. Agus menyayangkan, Indonesia justru tertinggal karena masih mengadopasi proyek-proyek dam berbiaya mahal yang justru merusak ekologi sungai hingga saat ini.
Agus menyadari pentingnya ilmuwan punya perspektif dan pengetahuan lintas dispilin ilmu (multidisplin) tidak hanya satu disiplin ilmu (monodisiplin) atau ilmu teknik bangunan saja dalam menyelesaikan masalah sungai. Solusi atas masalah sungai seringkali hanya menggunakan perspektif teknik bangunan, meninggalkan wawasan ekologis dan sosial.
Saat ia kembali dari Jerman, ia menghadapi perang gagasan dengan teknokrat atau ahli teknik yang konsepnya hanya membangun dam dan talut, tanpa melihat dampak secara ekologis dan sosial.
“Monodisiplin murni kalau diminta menyelesaikan persoalan sungai, munculnya gambar talut. Diajak diskusi ekologi, berkilah ‘bukan saya, saya tidak tahu’, sosial juga tidak tahu. Monodisiplin itu sifatnya destruktif,” kata guru besar bidang Sumberdaya Air dan Lingkungan itu.
Agus mengenang cerita bagaimana keyakinannya soal multidisiplin ilmu dalam menyelesaikan masalah sungai, terbangun karena pengalaman masa lalunya.
Sebagai orang teknik, ia menempuh pendidikan tentang water resources management di Jerman. Kala itu calon istrinya yang sama-sama kuliah di Jerman belajar ilmu sosial tentang pemberdayaan masyarakat. Agus mengaku terpapar perspektif sosial dari calon istrinya. Keseluruhan pengalaman tersebut membentuk pandangan Agus tentang sungai dan pentingnya multidisiplin ilmu dalam menyelesaikan masalah hingga saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News