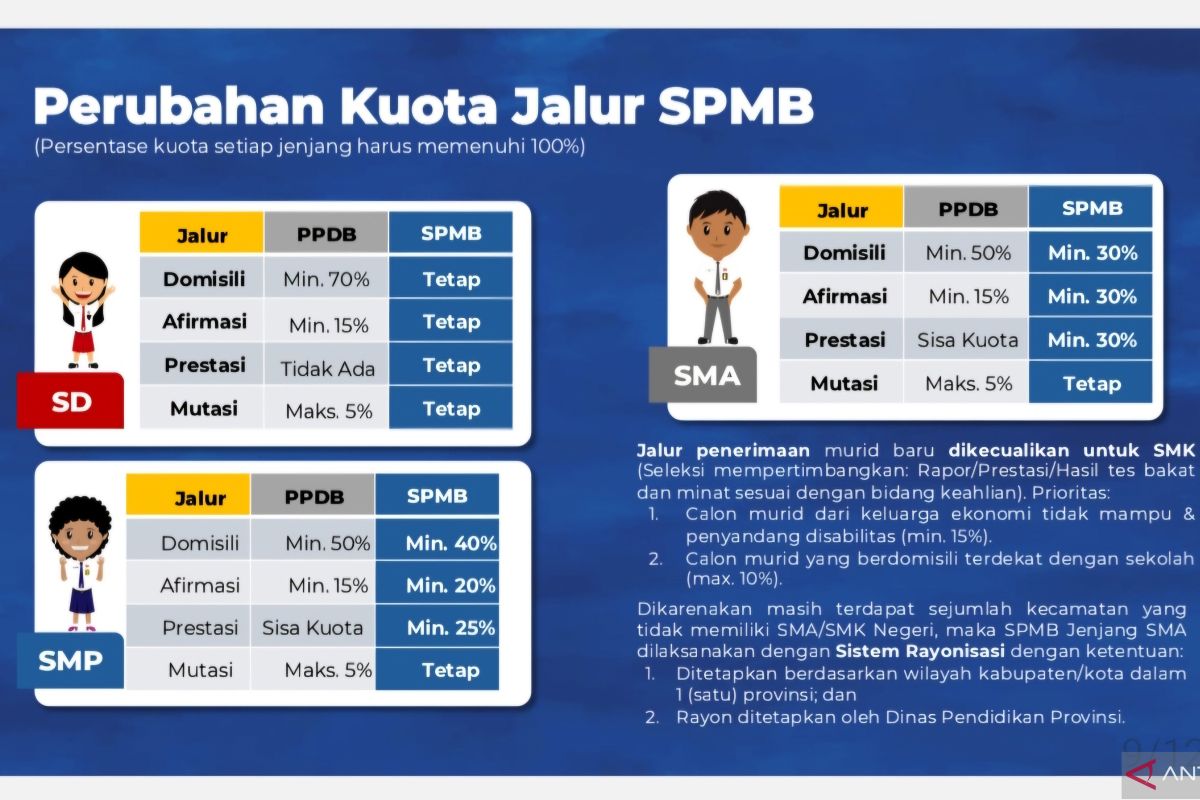Fenomena cancel culture terhadap artis dan tokoh publik yang dianggap berpihak pada pemerintah dinilainya sebagai bentuk teror nyata.
Kamis, 17 Apr 2025 08:03:19

Tahun pertama Pemerintahaan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan berat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan adanya fenomena cognitive warfare atau perang kognitif yang saat ini semakin mengemuka di ruang publik, khususnya media sosial.
Dia membeberkan bagaimana narasi yang sarat kebencian, fitnah hingga disinformasi membanjiri kanal digital. Sehingga menciptakan realitas semu yang memojokkan pemerintah.
Fenomena perang kognitif juga tampak dari ketimpangan standar dalam menyampaikan opini. Hasan menilai, saat pemerintah mencoba menyampaikan pandangan atau meluruskan kesalahan, langsung dituding tidak demokratis.
Hasan menjelaskan bahwa cognitive warfare tidak selalu merupakan hasil orkestrasi sistematis, namun bisa menjadi gejala menular. Fenomena ini bisa menjadi sangat berbahaya, sebab dampaknya nyata.
Dia juga menyoroti adanya tekanan terhadap masyarakat yang secara terbuka mendukung pemerintah. Fenomena cancel culture terhadap artis dan tokoh publik yang dianggap berpihak pada pemerintah dinilainya sebagai bentuk teror nyata.
Dalam menghadapi perang kognitif ini, Hasan menyatakan bahwa pemerintah harus bersikap lugas, terutama dalam mematahkan logika yang menyesatkan dan menyerang pokok-pokok argumentasi yang tidak berdasar.
Berikut catatan lengkap wawancara dengan Hasan Nasbi di Podcast Merdeka:
Bagaimana PCO menganalisis konten isu di media sosial. Karena kalau kita lihat ruang media sosial, misalkan ada yang pro kontra?
Jadi banyak sekarang orang yang itu gelisah karena badai dalam secangkir kopi, gelisah ketika melihat badai dalam secangkir kopi. Jadi ketika masuk ke salah satu platform media sosial itu kan memang platform itu isinya kemarahan, kebencian, fitnah itu aja isinya. Bahkan yang punya (akun) juga ikut berantem di situ, menyalurkan tempat marah-marah aja sini gitu. Tapi kalau kita masuk ke sana, wah pemerintah habis itu. Nah pemerintah habis tuh, pemerintah mana pun saya rasa ketika masuk di sana dan ngerasa itu dunianya di situ wah gelap dunia nih gelap dunia.
Nah tapi ini mungkin di Indonesia penggunanya hanya 4 atau 5 persen saja, sangat spesifik. Dan satu orang bisa punya mungkin 100 atau 10 akun. Dia berdebat sama diri dia sendiri, dan bahkan bisa dengan bot. Tapi kalau kita baper, masuk ke dalam yang seperti ini, kita akan ngelihat wah kiamat dunia nih, enggak ada yang baik nih, di negara manapun. Di negara yang aksesnya bisa dibuka enggak ada yang baik nih dunia ini.
Sama di Semua Negara?
Sama si di semua negara yang ada yang ini bisa dibuka iya gitu ini kan enggak pernah baik nih. Karena memang bawaan kayak pressure group itu, ketika masuk sana tuh kalau baik-baik enggak laku kita, kita harus marah-marah kayaknya masuk platform itu. Makanya saya minta dari awal, saya tidak mau terima laporan sosial media monitoring hanya dari platform ini. Saya maunya semua platform yang penting bahkan harus platform yang lebih besar Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Karena yang makin besar, dia makin mendekati masyarakat, kalau yang kecil ini.
Dan memang kemarahan itu walaupun di tempat lain itu juga ada kemarahan, tapi kemarahan di sini tuh kayak warnanya kemarahan memang. Kemarahan, kebencian, fitnah segala macam tuh di sini tuh disinformasi di sini semua tuh tapi di sini tuh ada perimbangannya. Ada yang suka, ada yang ngasih beritanya, ada yang segala macam itu sama-sama lakunya gitu loh.
Yang baiknya juga laku, bahkan ceramah agama juga laku laku di sana. oh ini lebih mendekati lebih mendekati realitas masyarakat makanya kita pantau. Nah kalau kita pantau itu, perasaan kita jauh lebih tenang. Ketika dapat itu perasaan kita jauh jauh lebih tenang.
Begitu juga dengan media. Media itu juga sorry ya kalian kan media, ada juga yang benar-benar ngejar clickbit. Kalau ditanya, "Bro kenapa begini?" Ya kalau enggak begini kita enggak laku Bang. Kalau begini kita enggak ada yang baca katanya. "Loh maksudnya enggak ada yang baca tuh gimana kalau harus begini gitu?"
Sadar enggak orang bisa marah dengan misalnya half truth. Hanya membaca secuplik judul kemudian di-capture kemudian dilempar di media sosial. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh bisa membuat orang salah memahami. Nah tapi saya juga senang ada media-media yang mau bertahan dan mungkin percaya bahwa dengan memberikan judul yang benar; pemahaman yang utuh; kesimpulan yang utuh; mungkin ia tidak langsung tinggi pembacanya, tapi orang akan jadikan dia referensi yang bisa dipercaya.
Kutipannya akurat, kutipannya enggak dimain-main, enggak satu kutipan satu kalimat dibagi dua ada loh. Satu kalimat dibagi dua gitu satu palingnya di sini satu kalimat lain dibagi di belakang terus dia framing lah tuh connecting the dot-nya jadi framing gitu loh. "Oh begini cara mainnya" Nah kita analisis itu juga dan kita lihat dan kita kan tahu media-media oh kayak gini mungkin dia memang mau mencari traffic tapi belum tentu bisa dipercaya kan? Tapi ada orang yang sudah percaya diri dia enggak mau cari traffic, bukan enggak mau cari traffic, butuh traffic tapi dia percaya diri bahwa dengan memberitakan yang benar orang akan tetap baca, orang akan tetap cari berita dan jadikan mereka referensi
Soal media sosial sebenarnya yang paling ngerinya kan impact-nya sih? Kalau misalkan ada program-program pemerintah yang seharusnya terinfo atau terframing enggak kurang tepat itu kan juga menjadi PR?
Makanya ini ada konsekuensi, saya enggak mau bilang demokrasi jelek, tapi kan selalu ada side effect side effect. Ketika kita buka nih, kita kan komit nih ada Undang-Undang tentang HAM, ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, ada Undang-Undang tentang pers, ya kita kan komit untuk soal kebebasan berbicara. Kita komit untuk kebebasan mendapatkan informasi, kita komit juga untuk kebebasan memberikan menyampaikan informasi, tapi masalahnya sekarang dengan kebebasan yang seperti ini enggak semuanya legitimate untuk menjadi penyampai informasi kan?
Dan bahkan banyak orang-orang yang viral itu, dia viral bukan karena dia legitimate sebagai sumber informasi tapi karena lebih kreatif aja sebagai sumber informasi. Dan orang percaya dan ini yang bisa menimbulkan banyak sekali. Dan apalagi sekarang, menurut saya, ada gejala-gejala yang itu yang pernah saya sebut sebagai cognitive warfare itu. Yang pokoknya orang bangun tidur harus benci sama pemerintah. Orang bangun tidur harus temukan minimal satu kesalahan pemerintah hari itu. Orang bangun tidur harus bisa membuktikan bahwa pemerintah hari itu jahat.
Ada yang mengorkestra itu?
Saya tidak tahu ada yang mengorkestra itu, tapi kan bisa juga jadi gejala menular kan.
Contoh yang paling simpel perang kognitif?
Contoh yang paling simpel bahwa kalau yang bukan pemerintah boleh ngomong apa aja. Bahkan termasuk kalau media boleh ngomong apa aja boleh menyebut apa aja bahkan ngeledek menghina juga boleh. Kemarin ada tayangan podcastnya salah satu media menyebut kantor komunikasi kepresiden sebagai Kikik. Kan KKK terus mereka tulis mereka sebut sebagai Kikik yang suka bocor di jalan itu. Lah sekarang pertanyaan saya kalian kan orang media, media perlu perlu etika enggak dalam berbahasa? Boleh enggak menghina lembaga negara? Itu ngeledek enggak? KKK dibilang Kikik? Menghina.
Misalnya nama orang sudah jelas-jelas, mungkin nama kecilnya Mulyono tapi dengan maksud menghina kamu sebut Mulyono aja. si Muliono ini bisa enggak media kayak gitu? Apakah media boleh kayak gitu tapi pemerintah kalau ringan sedikit bahasanya dianggap agresif dan tidak beretika? Kalau pemerintah keluar dari bahasa formal kemudian dianggap tidak. Ini perang kognitif nih kami boleh berbahasa apa saja kamu enggak boleh.
Sama kayak pemerintah, bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, dia marah, oh kamu bilang saya anjing. Padahal kalau kelas kita masuk kelas bahasa Indonesia, peribahasa kan enggak letter lag-nya kita enggak dipotong satu kata aja gitu kan ini kan ada maknanya. Kalau saya bilang serigala berbulu domba, bukan berarti kamu serigala atau domba, namanya peribahasa. Kalau saya bilang kamu katak dalam tempurung, bukan kamu katak, tapi ada maknanya yang kita pakai. Itu marah mereka, oh pemerintah ini enggak sopan pakai peribahasa, anjing menggonggong kafil beralu berarti rakyatnya dianggap anjing.
Tapi kalau ada mahasiswa atau demonstran lagu menyebutkan presiden dengan kata-kata 'a' titik-titik nama binatang, mereka bilang kebebasan berekspresi. Ini perang kognitif, mereka boleh semuanya pemerintah enggak boleh. Bahkan pemerintah ini kalau bisa jadi samsak aja, dipukulin terus, nangkis juga enggak boleh. Kalau nangkis dianggap membungkam kebebasan berbicara. Ini belum ngelawan nih, nangkis saja dianggap membungkam kebebasan. Ini perang kognitif, dia membentuk kesadaran baru mana yang boleh dan mana yang enggak boleh.
Ini yang paling banyak kan memang media sosial sebenarnya, apa ini organik apa ada yang mengorkestra karena gini?
Menurut saya, mungkin bukan soal orkestrasi, tapi ketika difasilitasi dia menjadi menular. Sama kayak ketakutan kan, bisa menular. Kebencian juga bisa menular. Kemarahan juga bisa menular.
Jadi media sosial berbahaya? Karena bisa menularkan kebencian
Karena bisa menular kan, makanya harus dilawan. Persoalan sekarang ketika pemerintah melawan narasi itu, mematahkan narasi itu dianggap membungkam kebebasan berbicara, dianggap tidak empati. Dianggap tidak terima kritik, loh kita mau meluruskan kita sama-sama ini kok kamu membentuk pikiran kita juga lagi membentuk pikiran.
Antara kritik sama fitnah itu berapa persentasenya?
Kalau jumlah, kalau di media sosial iya, kritik itu biasanya sepi. Tapi kalau udah dibumbuin sedikit aja kebencian tuh viral, bisa itu. Kita terima loh kritik, enggak pernah loh ditelepon wartawan, misalnya ada keracunan di sekolah mana gitu soal MBG, fakta dan ini harus diperbaiki. Itu enggak diapa-apain. Tapi ada satu media waktu itu nulis, ini wartawan senior nulis, ada yang meninggal habis menyantap makan bergizi gratis di Sukabumi. Kita tuh pusing loh telepon sana sini loh. Polres kita telepon, rumah sakit kita telepon, sekolah kita telepon, dapur MBG-nya kita telepon, enggak ada yang mati.
Terus gimana caranya nih? Ya udah kita telepon medianya, ini tulisan dari mana nih asalnya? Terus wartawannya bilang "Saya juga enggak tahu dapat inspirasi dari mana nulis itu." Dia sudah 20 tahun berkarir loh, dipecat akhirnya. Kalau di media sosial yang dimakan yang viral. Ini viral juga nih misalnya keracunan itu lumayan viral, tapi yang mati tadi waduh viralnya. Siapa yang ngobatin itu?
Sementara pemerintah hanya boleh klarifikasi. Kalau kita klarifikasi yang tadi viral yang ini soal itu mungkin 5 juta misalnya, kita klarifikasi yang nonton 1.000-2.000 kan begitu. Sementara pemerintah hanya boleh klarifikasi, hanya boleh menjelaskan, hanya boleh hak jawab. Kan ini harus dilawan.
Kedua, pemerintah ini kan punya pendukung. Ya kan dia enggak bisa jadi pemerintah kalau dia enggak punya pendukung yang banyak. Dia kan terbukti memenangkan perasaan dan pilihan masyarakat hampir 100 juta pendukungnya, 96 juta, tapi hampir hampir 100 juta. Kalau kita diskon 10% masih berapa? Masih 90 juta. Diskon 20% masih 80 juta. 80 juta ini mulai ngelawan enggak harusnya melawan argumentasi yang menggaduhkan pemerintah boleh kan? Tapi ketika mereka melawan buzer. Pendukungnya banyak loh, kamu yang sedikit loh.
Belum lagi cancel culture ya. Artis pendukung ini witch hunter, artis pendukung ini pokoknya di-cancel lah ditolaklah atau kalau perlu enggak usah dipromosiin kalau enggak dipressure lah. Ini teror loh. Ini teror loh terhadap kehidupan orang-orang yang kemudian memilih 02 itu kan enggak dosa. Ini perang kognitif loh, jadi seorang-orang dibikin merasa berdosa karena memilih 02. Dan banyak yang merasa ada pure good pressure, aduh gua minta maaf deh. Habis minta maaf, dibully maaf lu enggak diterima katanya.
Itu teror loh, tapi kita enggak boleh nyebut mereka teror. iya nah kalau kita ngelawan, ini dibilang wah ini pembungkaman. Nah itu yang disebut witch hunter itu bahwa saya sekarang pemerintah masa enggak boleh ngelawan pikiran-pikiran kayak gini. Masa pendukung pemerintah juga enggak boleh ngelawan pikiran-pikiran kayak gini. Harusnya yang cancel itu yang banyak cancel yang sedikit, ini yang sedikit meng-cancel yang banyak.
Bagaimana pemerintah melawan fitnah atau hoaks?
Makanya ketika kita bicara lebih lugas, mematahkan argumentasi, membatalkan logika, menyerang pokok argumentasi harusnya fair dong. Kan pikiran lawan pikiran nih. Tapi ketika kita lakukan itu dibilang enggak punya empati, dibilang anti kritik, dia bilang "Loh kenapa Anda boleh berbicara seperti itu, kita enggak boleh meluruskannya?" Kita kan meluruskan. Kita kan enggak maki-maki mereka. Sementara mereka maki-maki loh.
Kita kan enggak merendahkan mereka, sementara mereka merendahkan. Tapi pokok logikanya, pokok argumentasinya kita serang dong. Kalau Anda salah ya kita bilang salah. Kalau Anda terbalik logikanya, kita bilang terbalik logikanya. Ketika ini mungkin pelan-pelan bisa saja diterima bisa saja enggak, tapi saya punya pendirian nih kalau pemerintah enggak ngelawan ini pemerintah jadi samsak.
Tudingan soal buzzer pemerintah?
Kalau pemerintah beriklan di media boleh enggak? Di media sosial enggak boleh? boleh enggak mengiklan? Kalau ada akun personal yang misalnya bisa mempromosikan capaian pemerintah boleh enggak? Mereka punya kewajiban enggak untuk itu (menuliskan sponsor)? Berarti perlu dibikin kode etik kan? Mereka enggak diwajibkan untuk itu, maksudnya kesalahan tuh bukan di mereka gitu loh.
Di media boleh kan placement iklan di media boleh kan? Gitu sebenarnya itu boleh kecuali misalnya pemerintah bayar orang buat berantem, buat memecah belah, iya buat mendiskreditkan orang itu dari anggaran itu kalian boleh kritiklah. Tapi kalau pemerintah mempromosikan capaian-capaian lewat platform lewat endorser, lewat KOL itu sama sahnya, kalau menurut saya, dengan pemerintah mempromosikan capaian di media gitu sama aja.
Menurut saya kayak gitu, jadi jangan langsung dibilang ini punya bazer. Bahkan yang pendukung yang enggak ngapa-ngapain nih, enggak punya kontrak, enggak ada placement iklan segala macam, ketika dia muji pemerintah (dibilang) bazer bazer gitu. Saya juga sepanjang tahun dianggap bazer gitu.
Sejak kapan sih menyadari soal perang kognitif ini?
Kalau sadarnya sudah lama, tapi punya namanya baru. Kita sadarnya sudah lama ini soal perang kognitif ini, tapi punya namanya baru gitu loh. Suatu saat, saya di satu sesi jadi pembicara dengan juru bicara Kemenhhan Brigjen Frega Inkiriwang. Nah dia tuliskan itu level-level perang informasi, sampai di puncak namanya perang kognitif. Terus dia jelasin. Oh yang kita bayangkan selama ini itu namanya adalah cognitive warfare, perang opini, perang informasi tidak hanya perang psikologis. Oh namanya. Jadi sudah tahu orangnya lama, tapi tahu namanya baru. Selama ini belum kenalan namanya siapa gitu nah baru tahu namanya setelah berapa saat yang lalu.
Tujuan dari adanya perang kognitif? Dan siapa di balik itu semua?
Bukan dengan tujuan tunggal mungkin, tapi intinya menjutkan pemerintah di corner pemerintah di tempat yang dia enggak bisa gerak. Nanti jadi jelek, nanti jadi jahat, kalau perlu tumbang sekalian. Level-level tujuannya sampai di sana menyandung atau sudah tumbang enggak bisa gerak apa-apa. Pemerintah begitu dapat tekanan publik itu jadi mikir loh. Bayangin coba efisiensi aja di demo coba. Bukannya senang efisiensi, tapi efisiensi ada yang demo loh.
Efisiensinya Rp300 triliun loh. Dengan kabinet nambah ini berapa sih? Yang efisiensi tuh Rp300 triliun. Kasih makan bergizi gratis aja itu banyak sekali yang sinis, dibilang ini kampanye buat 2029 itu ada tuh satu intelektual bilang "Makan bergizi gratis menghabiskan dana segini ini kampanye yang besar sekali biayanya." Nah kasih makan anak dan ini dilakukan oleh lebih dari 105 negara. Kamu mau bilang 105 negara itu kampanye buat 2029? Ini cara ngelawan cognitive warfare tuh begini gitu. Ini bukan agresif gitu, ketika saya bilang "Kamu mau bilang 105 negara itu yang kasih makan anak-anak sekolah itu sebagai kampanye 2029." Kan ininya harus dipakai ada logika yang benar. Ini separuh logika disampaikan ke publik tapi karena disampaikan dengan kemasan yang menarik atau oleh orang yang kira-kira punya otoritatif, orang yang kira-kira punya otoritas. Kemudian saya mau serang itu, walaupun risikonya dianggap agresif enggak layak nih jadi jubir.
Tujuannya mungkin enggak satu, level-levelnya macam-macam. Bisa menyandung, bisa menghambat, sekedar menjelek-jelekan atau menjatuhkan. Kalau guliran bola saljunya makin lama makin besar kan apa saja bisa terjadi. Kalau guliran kebencian yang jadi bola salju kan apa saja bisa terjadi. Kalau ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu bergulir terus-menerus kan apa saja bisa terjadi.
Inilah pentingnya kita sadar bahwa ada namanya cognitive warfare. Kita belum memasukkan aktor-aktor dari luar loh, misalnya pasti ada kan aktor dari luar yang enggak suka Indonesia maju pasti ada kan? Kalau kita kompak cepat kita majunya. Cina itu kan kompak maju cepat dia. Singapura kompak cepat dia majunya. Kita kan jarang kompaknya gitu, jadi larinya lari kesandung dikit. Lari kakinya keseleo. Gitu-gitu kita kalau lagi lari itu. Nah ini yang harus kita hadapi itu hanya bisa kita hadapi kalau kita sadar.
Bahwa pola komunikasi hari ini enggak bisa lagi hanya press rilis, enggak bisa lagi hanya hak jawab, klarifikasi, konfirmasi itu perlu. Tapi men-challenge argumentasi orang yang menyudutkan pemerintah juga penting. Supaya masyarakat bisa pilih, oh ya ini argumentasinya ini, ini argumentasinya ini. Ini kalau ibarat senjata, cognitive warfare itu minimal pakai basoka. Kalau press relase itu pistol air. Maksudnya, kita hanya boleh pakai itu sementara mereka pung pung pung pung meledak gitu loh. Menang enggak kira-kira?
Kalau begitu pemerintah pasti lama-lama tersudutkan kalah. Kalau kebencian dan ketidakpercayaan bergulir semakin besar apa saja bisa terjadi. Jadi ini kan ide, proposal, rencana yang bisa saja disetujui bisa saja tidak. Tapi sebagai sebuah bentuk kepedulian dan bentuk usaha untuk membuat pemerintah bisa menjalankan program-programnya dengan baik, menurut saya, memang kita harus punya kesadaran cognitif warfare. Bukan memerangi orang-orang. Karena mereka rakyat Indonesia juga, tapi memerangi narasinya. Artinya agar ada narasi, bisa dua, tiga, empat pandangan biar mereka bisa pilih.
Artikel ini ditulis oleh


Mari Dukung Jurnalisme Berkualitas: Lawan Hoaks, Misinformasi dan Disinformasi
Periksa fakta lebih dulu sebelum berpikir dan mengambil sikap. Ini penting dilakukan agar tidak terjebak dalam kubangan kekeliruan.

Masyarakat Diajak Bijak dan Kritis Hadapi Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024
Masyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Hoaks 2 tahun yang lalu

Tangkal Hoaks Terkait Pilkada dengan Literasi Digital
Peningkatan akses informasi lebih mudah, memilih sumber informasi yang kredibel, hingga menganalisis data dari berbagai sudut pandang dirasa sangat penting.